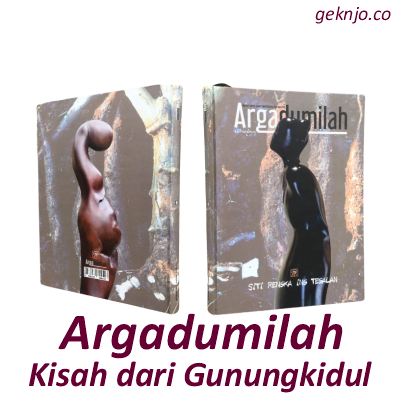Judul buku: Argadumilah, Narasi-narasi Sederhana tentang Gunungkidul
Penulis: Tugi Widi, dkk
Penerbit: CV Handayani Diva Media
Tahun Terbit: 2020
Jumlah Halaman: vi+241 halaman
“Setidaknya ada 2 perkara penting yang melingkupi kehidupan para petani tradisional Jawa, termasuk Gunungkidul. Pertama, perkara mitologis Dewi Sri. Kedua, benda tradisional lesung dan alu…”
-Tugi Widi, 2020
Kutipan di atas saya baca di pramula Argadumilah: Narasi-narasi Sederhana tentang Gunungkidul. Tugi Widi, salah satu nama penulis esai yang termaktub dalam Argadumilah menyebut bahwa kehidupan masyarakat Gunungkidul selaras dengan beragam mitologi.
Ya, terdapat beberapa penulis yang mengikat dirinya dalam buku itu. Mereka berbisik-bisik lewat kata-kata, menceritakan hal-hal asik versi loka carita. Barangkali, nyaris delapan puluh persen cerita-ceritanya belum sempat ditulis. Wajar, manusia terlampau sering silau dengan hal-hal mayor dan yang minor kerap dianaktirikan.
Segenap tulang, otot, dan saraf pada jari-jari kita sudah lebih dari cukup untuk menulis apa saja, ujar Wislawa Szymmborska dalam salah satu puisinya. Pun termasuk perihal menulis sebuah kutipan milik Tugi Widi di atas.
Kutipan saya sematkan itu masih relevan dengan kehidupan masyarakat Gunungkidul. Mengingat mayoritas masyarakat Gunungkidul masih menggantungkan kehidupan sehari-hari dalam sektor pertanian. Sebuah kutipan yang mengetuk mulabuka Argadumilah, Narasi-narasi Sederhana tentang Gunungkidul. Buku ini berisi enam belas esai, membahas ihwal beragam narasi-narasi lokal Gunungkidul.

Upaya-upaya penulisan buku ini dilatarbelakangi atas perlunya ulasan ulang “ingatan” dan “tuturan” masa lalu. Berbeda dengan kenangan, ihwal ingatan dan “me-ngi-ngat” (kata kerja), itu perlu dilatih saban hari. Sebab, “mengingat” adalah semacam upaya-upaya kecil menyibak galih dan identitas keberadaan suatu entitas: makhluk, benda, suara, warna, rasa, dan seterusnya.
Terkadang, masyarakat lokal tak memiliki kesempatan untuk menceritakan dirinya sendiri. Mereka sibuk urusan primer yang sah: sandang, pangan, dan papan. Akibatnya, banyak anasir tafsir dari luar wilayah yang memancang metodologi riset yang instan: pengamatan cepat, satu, dua, tiga, empat, hingga beberapa hari saja. Hal yang sah dan umum, tapi simplifikasi tafsir dengan kurun yang sebentar tentu cukup berisiko: tafsir ugal-ugalan, validitas data, serta hasrat mengkoloni yang selalu dan akan selalu ada. Tak adil.
Saya tertarik dengan buku Argadumilah karena buku ini ditulis oleh para-para kulawarga lokal. Mereka mendiami Gunungkidul tak cukup satu, dua, tiga hari saja. Secara sadar, mereka paham bahwa pengetahuan lokal pantas dan perlu untuk dituliskan. Tentu tak kalah pentingnya dengan pengetahuan nasional cum global: tentang fafifuwasweswos yang terkadang jaraknya sangat jauh dengan reealita sekitar. Setidaknya mereka-mereka yang menulis buku “sempat” tinggal setahun, dua tahun, hingga puluhan tahun di Gunungkidul.
Mereka melihat perubahan tanah-lahir secara langsung. Setidaknya, kulawarga itu bisa mengomparasi keadaan Gunungkidul tempo lalu dengan saat ini. Perbedaan-perbedaan ini tersaji dalam dua pilah: positif dan negatif. Komparasi menghasilkan simpul-simpul minor atau mayor, ihwal dampak yang baik bagi Gunungkidul, begitupun sebaliknya. Semacam menimbang hal—hal yang timpang.

Tentu tak semua hal tentang Gunungkidul terbahas tuntas lewat buku ini. Perlu jibunan waktu dan kertas untuk mendokumentasikan segala hal tentang Gunungkidul. Buku ini “hanya” bagian kecil dari seluruh budaya, adat, tradisi, dan pengetahuan lokal menyangkut Gunungkidul.
Beragam tema tersaji dalam buku ini: mitologi, ekologi, gender, sejarah, dan sebagainya. Buku ini penting untuk dibaca. Mengacu judul buku, khususnya kulawarga Gunungkidul sekalian, barangkali beberapa di antara kita, telah melupakan nama Argadumilah. Tergesut oleh beragam istilah-istilah baru nan kekinian.

Mungkin, penamaan-penamaan tempat dan gaya hidup harus menyelaraskan dengan spirit nut kelakoning jaman: penamaan-penamaan di masa lalu seolah “wajib” digantikan oleh penamaan baru yang lebih wangun. Dan, diksi “wangun” pun menjadi benar berdasar versinya masing-masing. Toh, perihal kesadaran wilayah bukanlah perkara wajib dalam hidup ini.
Buku setebal 241 halaman ini memuat beragam istilah lokal Gunungkidulan. Istilah-istilah yang lekat dan dekat, seolah manusia-manusia Gunungkidul enggan berjarak dengan tanah-air-nya. Pun dalam membantu pembaca menafsirkan Gunungkidul, penyusunan buku ini dilengkapi dengan beragam gambar dan foto.
Mayoritas foto yang disajikan dalam buku ini terdiri dari berbagai unsur: manusia, hewan, dan alam. Di muka buku, misalnya, tergambar foto gerabah. Masuk dalam lembar-lembar isi buku, setiap esai memiliki visual yang mewakili ide-gagasan esai: petani, gunung, tumbuhan, hewan, penari, dan sebagainya.

Bagi beberapa orang, Gunungkidul tak begitu penting untuk ditelaah lebih lanjut. Jikapun penting, biasanya membahas ihwal problem-problem jelmaan shadow bullying: udik, kering, miskin, panas, susah air, pulung gantung, dan UMR rendah.
Namun, di lain sisi, Gunungkidul dirasa penting untuk didokumentasikan. Sebab, presentase luas wilayah Kabupaten Gunungkidul nyaris separuh dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara wilayah saja sudah lumayan hegemoni. Belum lagi dalam hal kebudayaan, foklor masih sangat mudah dijumpai. Tapi, bila tak didokumentasikan dengan baik. Segala hal yang menyangkut identitas cum kebudayaan akan punah.
Meski dikenal dengan wilayah pegunungan kapur yang kering, di wilayah Gunungkidul (utamanya) area Batur Agung dan Ledoksaren terdapat hamparan sawah padi dengan irigasi. Satu kata “padi” memuat banyak turunan-turunan “kata” setelahnya. Kata-kata itu saling topang, gotong-royong satu dan lainnya. Padi tak berdiri sendiri, ia didukung air, alat-alat pertanian, hama, masyarakat, dan kelak menjadi adat istiadat, budaya, ataupun ritual. Segala berkaitan dengan sangkan paraning dumadi.
Beberapa wilayah kecamatan sentra penghasil padi di Gunungkidul adalah Semin, Gedangsari, Patuk, Ngawen, Ponjong, dan Karangmojo. Terdapat 6 wilayah utama penghasil sawah tadah hujan adalah Saptosari, Panggang, Semanu, Wonosari, Karangmojo, dan Playen.
Membicarakan padi selaras dengan memikirkan ibu bumi. Berpikir tentang “ibu” bumi sejurus dengan kesuburan, gemah-ripah, dan rasa cinta kasih. Buku Argadumilah menjadi contoh atas kulawarga yang sama-sama mencintai tanah-lahir.

Tak ada karya yang tak lepas dari kritik. Serupa hal itu, buku ini juga dirasa perlu ditimbang dan dipikirkan. Pengetahuan lokal yang diikat dan disajikan dalam bentuk esai ini terbilang bagus. Hanya saja, kulawarga Gunungkidul yang nyerat buku ini masih didominasi oleh mas-mas, pakde-pakde, paklek-paklek sedang mbak-mbak, bulek-bulek, budhe-budhe-nya terhitung sedikit. Begitu.
Penulis: Sintas Mahardika
Editor: Bagong Gugat
Salah satu warga Gunungkidul. Hobi jalan kaki, arsiparis jalanan, dan suka foto.
Oleh : Sintas Mahardika