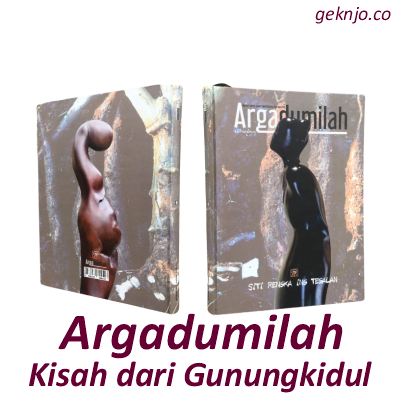Reyog Dhodhog mlampah saking balai dusun dumugi balai desa. Unine, pong jing pong pong jing pong jung. Bocah cilik padha nunggang-nyasak galengan, arah mlayune mbelah kebonan, amarga pingin ndelok gunungan. Budhe Sri nggendong putu, unjuk donga sinambi ndulang sega. Bakul es, bakul plembungan ya semana uga, ngundhuh berkah, nusulke rasa.
(Bagong Gugat, 2025)
Asal Usul Nama Reyog Dhodhog
Reyog berasal dari kata “Rog,” yang memiliki kesamaan arti dengan “Reg” dan “Yog,” yakni bergerak atau berguncang. Nama Reyog Dhodhog atau Reyog Prajuritan diambil dari karakteristik tokoh, koreografi, dan alat musik pengiringnya. Kata “Dhodhog” merujuk pada kendhang Dhodhog, instrumen khas yang menjadi pengiring utama dalam pertunjukan ini. Kendang Dhodhog adalah beduk kecil berbahan kayu jati, yang hanya satu sisinya saja yang ditutupi kulit.
Selain dikenal sebagai Reyog Dhodhog, kesenian ini juga disebut Reyog Prajuritan karena karakteristik pertunjukan yang menonjolkan figur prajurit, gerak tubuh yang mengimitasi gerak prajurit, dan juga alur cerita keprajuritan. Ada beberapa karakter penting yang ditampilkan dalam pertunjukan Reyog Prajuritan, antara lain: Udheng Gilig, Panombak, Panyongsong, dan Jaranan.
Menurut kamus bahasa Jawa, penulisan yang benar untuk seni tradisional ini adalah “Reog”. Namun, dalam aksara Jawa, ejaannya menjadi “Reyog” (ꦫꦺꦪꦺꦴꦒ꧀). Perubahan ini mencerminkan kebiasaan penulisan masyarakat Jawa yang lebih mengimitasi pelafalan lisan. Proses fonologis ini akhirnya menghasilkan ejaan yang berbeda, tetapi tetap merujuk pada bentuk kesenian yang sama.
Penambahan huruf “Y” dalam ejaan “Reyog” tidak menjadi masalah karena istilah Reyog tidak memiliki padanan kata lain dalam bahasa Jawa. Secara morfologis, penambahan ini bukan merupakan proses infiksasi. Sehingga tidak mengubah makna dasar kata. Oleh karena itu, baik “Reog” maupun “Reyog” dipahami sebagai nama yang merujuk pada bentuk kesenian yang sama.
Sejarah Reyog Dhodhog: Narasi Majapahit dan Pengaruh Keraton Yogyakarta
Reyog Dhodhog terus bergerak, baik melalui bentuk pertunjukannya maupun melalui narasi sejarah yang menyertainya. Namun, hingga kini, para sejarawan belum mencapai kesepakatan mengenai kepastian sejarah Reyog Dhodog. Berdasarkan berbagai literatur seperti Rebowagen.com, Seputargk.id, dan situs resmi Desa Bendungan, Reyog Dhodhog diyakini sebagai representasi sejarah perjalanan pasukan Majapahit yang mengembara ke Gunungkidul untuk mencari Raja Brawijaya V.
Validitas sejarah ini seringkali dikaitkan dengan jejak Majapahit lainnya, seperti petilasan Brawijaya di Pantai Ngobaran, asal-usul Kapanewon Playen yang berawal dari kandang kuda pasukan Majapahit, serta cerita babat alas Dewa Katong. Besarnya pengaruh narasi pelarian trah Majapahit ke Gunungkidul turut menggiring sejarah Reyog Dhodhog ke linimasa serupa, menjadikannya salah satu narasi populer yang diwariskan di Gunungkidul.
Selain narasi Majapahit, Reyog Dhodhog juga memiliki kaitan erat dengan Keraton Yogyakarta. Hal ini terlihat dari busana dan elemen estetika dalam pertunjukan Reyog Dhodhog terkini. Misalnya, penggunaan motif surjan dan jarik, bentuk udheng gilig yang menyerupai yang dikenakan oleh Prajurit Nyutra Keraton Yogyakarta, hingga bendera merah putih “dwaja dwiarsa” yang menjadi bagian dari properti tombak.
Meski sejarah saling tumpang tindih, tetapi sejarah tersebut dituturkan secara turun temurun oleh para sepuh atau among tani dari ke generasi ke generasi. Sehingga Reyog Dhodhog tidak kehilangan relevansinya. Keragaman narasi ini merupakan salah satu dari banyak indikasi bahwa teori-teori sejarah dari barat memiliki pandangan yang terbatas terhadap bidang produksi sejarah di Nusantara. Pengetahuan sejarah dari barat terlalu meremehkan ukuran, relevansi, dan kompleksitas situs-situs yang tumpang tindih di mana sejarah diproduksi, terutama di luar dunia akademis.
Jamaknya narasi pengetahuan sejarah dan bentuk pertunjukan yang selalu terkontekstualisasi memungkinkan penghancuran hierarki pengetahuan yang selama ini mengarak di tubuh bangsa. Atau, dalam bahasa yang ndakik-ndakik disebut dekolonisasi, usaha mendorong adanya pluriversality yang menawarkan pembentukan pengetahuan secara kombinatif-yang kemudian memungkinkan masyarakat lokal menentukan sendiri arah gerak kebudayaanya.
Mengenal Karakter dalam Pertunjukan Reyog Dhodhog.
Lazimnya, pertunjukan Reyog Dhodhog di Gunungkidul dimainkan oleh 16 penari. Pembagiannya terdiri atas:
- Dua orang Udheng Gilig
- Dua orang Panongsong
- Delapan orang Panombak/Prajurit Rontek
- Dua Prajurit Jaran Kepang
- Sepasang Penthul dan Tembem.
Mari mengenal masing-masing karakter Reyog Dhodhog !
Udheng Gilig
Udheng Gilig diposisikan di barisan terdepan sebagai pemimpin pasukan atau senapati. Nama Udheng Gilig berasal dari aksesori udheng berbentuk bulat melingkar dengan plisir emas yang dikenakan di kepala senapati. Untuk memperkuat figur senapati dalam tubuh Udheng Gilig, penekanan dilakukan melalui busana dan gerak. Busana yang dikenakan oleh Udheng Gilig meliputi:
- Celana panji (pendek)
- Jarik motif cinde
- Stagen
- Timang
- Sampur
- Kllat bahu
- Sumping
- Udheng
- Kacamata hitam (belor)
Prajurit Song-song / Panongsong
Song-song dalam bahasa Jawa Krama Inggil berarti “payung”. Prajurit Song-Song, atau yang lebih luwes disebut Panongsong, diposisikan tepat di belakang Udheng Gilig untuk memayungi sang senapati ke mana pun ia pergi, kecuali saat sang senapati berperang.
Kehadiran Panongsong yang selalu membersamai Udheng Gilig menandakan adanya kelas sosial dalam pertunjukan Reyog Dhodhog. Secara semiotik, song-song sendiri merupakan simbol kehormatan yang hanya diperuntukkan bagi figur terhormat. Hal ini menunjukkan bahwa Udheng Gilig adalah sosok yang paling dihormati dalam struktur pertunjukan Reyog Dhodhog.
Selain itu, perbedaan kelas sosial antara Udheng Gilig dan Panongsong juga ditekankan melalui busana yang dikenakan. Berbanding terbalik dengan kemewahan kostum Udheng Gilig, pakaian Panongsong lebih sederhana. Kostum yang dikenakan terdiri atas:
- Celana panji (pendek)
- Lurik
- Jarik
- Stagen
- Timang
- Sampur
- Blangkon atau iket
- songkok atau jamang
- hand property song-song (payung)
Prajurit Rontek
Prajurit Rontek, atau yang dalam beberapa paguyuban disebut Panombak, diposisikan di urutan ketiga dalam formasi barisan Reyog Dhodhog. Dari segi hierarki, Panombak berperan sebagai pengikut Udheng Gilig, sementara dari segi fungsi, mereka bertugas menyerupai infanteri terdepan atau garda terdepan pasukan.
Busana yang dikenakan Panombak mirip dengan Panongsong. Perbedaannya terletak pada hand property yang dibawa: Panombak membawa tombak yang dihiasi beberapa helai janur serta bendera merah putih (dwaja dwi warna).
Prajurit Jarang Kepang
Prajurit Jaran Kepang diposisikan di lapisan terakhir dalam formasi barisan Reyog Dhodhog. Sesuai dengan namanya, prajurit ini membawa hand-property berupa pedang kayu dan kuda-kudaan atau jaranan, yang umumnya terbuat dari anyaman bambu.
Berbeda dengan Panombak yang berfungsi sebagai infanteri, Prajurit Jaran Kepang lebih berperan menyerupai pasukan kavaleri. Selain karena memiliki “tunggangan”, gerakan prajurit ini juga lebih trengginas dibandingkan dengan prajurit lainnya.
Penthul dan Tembem
Penthul memiliki nama lain Bancak, sedangkan Tembem juga dikenal dengan sebutan Beles atau Doyok. Penamaan Penthul dan Tembem merujuk pada jenis topeng yang dikenakan oleh masing-masing karakter. Penthul memakai topeng berwarna putih, sementara Tembem mengenakan topeng hitam. Kedua topeng ini memiliki bentuk khas karena tidak menutupi area bibir, memungkinkan pemakainya tetap dapat mengekspresikan gerakan bibirnya saat tampil.
Kemunculan karakter Penthul dan Tembem juga erat kaitannya dengan berbagai kesenian lain, seperti Penthul Tembem dari Madiun dan Topeng Dhalang dari Malang. Dalam pertunjukan Jaranan Thek Ponorogo, dua karakter ini ditokohkan sebagai Potrojoyo dan Potrolotho, yang merupakan punggawa kerajaan Bantarangin. Menariknya, jejak sejarah Penthul dan Tembem ternyata jauh lebih tua. Beberapa sumber menyebutkan bahwa karakter Bancak dan Doyok pertama kali muncul dalam cerita Panji pada era Kerajaan Kediri, jauh sebelum Gunungkidul, Ponorogo, dan bahkan Majapahit berdiri.
Meskipun memiliki berbagai penyebutan dan narasi sejarah yang berbeda di setiap daerah, Penthul dan Tembem tetap memiliki karakter yang serupa. Banyak literatur menyebutkan bahwa secara sifat, mereka mirip dengan figur Panakawan dalam pewayangan. Mereka berperan sebagai pamomong bagi para senapati dan prajurit. Secara semiotik, pasangan ini menjadi simbol keseimbangan hidup, layaknya malam dan siang, matahari dan bulan, yin dan yang, serta kehidupan dan kematian. Simbolisme ini ditampilkan melalui warna topeng, busana, dan karakteristik tubuh pemainnya.
Keunikan lain dari Penthul dan Tembem adalah peran mereka dalam menyampaikan kata-kata inspiratif selama pertunjukan berlangsung. Mereka kerap menyemangati, mengingatkan, atau memeriahkan suasana dengan celotehan khasnya. Oleh karena itu, tidak jarang ibu-ibu dalam pertunjukan meminta Penthul untuk mendoakan anak-anak mereka. Ritual ini biasanya dilakukan dengan mengusap sampur (selendang) Penthul ke wajah anak sebagai bentuk doa dan harapan baik.
Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa grup Reyog Dhodhog, Penthul biasanya diperankan oleh sosok yang paling memahami seni pertunjukan ini dan memiliki wawasan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan anggota lainnya. Sosok ini sering kali dianggap sebagai sesepuh, seseorang yang dihormati dalam komunitas Reyog Dhodhog. Kepercayaan tersebut kemudian berkembang menjadi consensus di masyarakat, memperkuat peran Penthul sebagai figur penting dalam seni pertunjukan tradisional ini.
Peran Wiyaga dalam Pertunjukan Reyog Dhodhog
Selain para penari, dalam seni Reyog Dhodhog, peran wiyaga (pemusik) juga sangat penting. Komposisi alat musik utama yang digunakan dalam pertunjukan ini terdiri dari:
Bendhe
Bendhe merupakan alat musik berbentuk gong kecil yang menghasilkan suara berdenting khas. Dalam pertunjukan Reyog Dhodhog, terdapat dua bendhe kecil dan satu bendhe besar yang digunakan untuk memperkaya irama.
Kecrek
Kecrek adalah alat musik berbentuk lempengan logam yang biasanya terbuat dari kuningan atau campuran besi dan kuningan (swasa). Fungsinya untuk memberikan aksen ritmis dalam pertunjukan.
Dhodhog
Dhodhog adalah alat musik utama dalam Reyog Dhodhog dan menjadi tajuk dari pertunjukan ini. Alat musik ini memiliki fungsi serupa dengan kendhang dalam karawitan atau drum dalam musik modern. Sebagai instrumen ritmis, dhodhog berperan dalam mengatur tempo dan dinamika irama pertunjukan.
Lagu-lagu dalam Pertunjukan Reyog Dhodhog
Dalam pertunjukan Reyog Dhodhog modern, lagu-lagu yang dibawakan semakin bervariasi. Selain lagu-lagu Jawa kuno, pertunjukan ini juga mengadaptasi lagu-lagu Jawa modern, seperti Caping Gunung (ciptaan Gesang, 1973). Bahkan, lagu anak-anak seperti Bintang Kecil (ciptaan R. Geraldus Daldjono Hadisudibyo) juga kerap dimainkan.
Keberagaman lagu dengan karakter dan era penciptaan yang berbeda ini membuat pertunjukan Reyog Dhodhog dapat dinikmati oleh berbagai generasi. Dengan adanya inklusivitas ini, pesan yang disampaikan dalam pertunjukan menjadi lebih luas dan dapat diterima oleh semua kalangan. Faktor inilah yang turut menjaga eksistensi Reyog Dhodhog hingga saat ini.
Struktur dan Alur Pertunjukan Reyog Dhodhog
Reyog Dhodhog memiliki alur naratif yang berpijak pada sistem karawitan dengan nada slendro. Pertunjukan ini dibangun oleh berbagai elemen seni, seperti gerakan khas (ngentrung dan pacak gulu), struktur lakon, komposisi gendhing, serta unsur estetis lainnya, termasuk tata rias, busana, karawitan, dialog, dan tembang.
Secara umum, alur pertunjukan Reyog Dhodhog terbagi menjadi tiga babak, yaitu:
- Babak Pembuka (pambuka)
- Babak Inti (babak utama)
- Babak Penutup (babak pungkasan)
Namun, pembagian ini bisa bervariasi tergantung pada masing-masing paguyuban yang menggelar pertunjukan.
Babak Pembuka: Formasi dan Simbolisasi
Pertunjukan diawali dengan masuknya para penari ke arena dengan gerakan khas lampah macak. Setelah sampai di tengah arena, mereka membentuk formasi arga pawaka.
Selanjutnya, prajurit melakukan formasi sembah—sebuah gerakan penghormatan yang divisualisasikan dengan posisi jengkeng (berjongkok). Gerakan ini melambangkan penghormatan kepada penonton dan pihak penyelenggara.
Setelah penghormatan, pasukan dibagi menjadi dua kubu, yang sering kali disimbolkan sebagai kubu hitam dan putih. Pembagian ini merepresentasikan dualisme dalam kehidupan manusia.
Babak Inti: Pertarungan dan Dinamika Musik
Babak inti terdiri dari tiga bagian utama:
- Perang Udheng Gilig
- Perang Prajurit Panombak
- Perang Prajurit Jaran Kepang
Dalam bagian perang Udheng Gilig, semua prajurit selain Udheng Gilig membentuk formasi melingkar, sementara Udheng Gilig menempati posisi di tengah arena. Ia kemudian bertarung secara bergantian, menjadi semacam “jagoan” dari masing-masing kubu.
Selama pertarungan berlangsung, wiyaga (pemusik) akan meningkatkan tempo irama. Suara benturan pedang sang senapati semakin diperkuat dengan bunyi kecrek, menciptakan efek suara yang dramatis.

Tokoh Penthul dan Beles juga berperan penting dalam babak ini. Mereka semacam “botoh” (penonton yang mendukung dan memberi semangat), serta “juru suwuk” (penyembuh) yang membantu sang senapati jika ia tersungkur agar dapat kembali bertarung.
Formasi melingkar yang digunakan dalam perang Udheng Gilig juga diterapkan dalam perang Panombak dan perang Prajurit Jaran Kepang. Meskipun ada sedikit variasi dalam koreografi, struktur alurnya tetap serupa.
Babak Pungkasan

Dalam babak pungkasan pertunjukan Reyog Dhodhog, para penari kembali ke formasi awal, menyatu sebagai satu kesatuan setelah sebelumnya terbagi dalam dua kubu. Mereka kemudian melakukan gerakan “ngentrung” saat meninggalkan arena pertunjukan, menandai akhir dari kisah yang disampaikan
Reyog Dhodhog Menyatukan Masyarakat dalam Perayaan Rasulan
Seni kerakyatan memiliki sifat yang adaptif dan fleksibel, selalu berkembang mengikuti demografi dan dinamika sosial terkini. Kehadirannya tidak hanya bertujuan sebagai hiburan semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Seni ini sering kali lahir dari dorongan kebutuhan rohani yang berkaitan dengan kepercayaan adat dan tradisi leluhur.

Salah satu contoh yang masih lestari hingga kini adalah pertunjukan Reyog Dhodhog di Desa Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, terutama dalam hubungannya dengan tradisi Rasulan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat modern sebagai Bersih Desa. Tradisi Rasulan merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat Gunungkidul atas hasil panen yang melimpah, sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta.
Di beberapa desa di Gunungkidul, pertunjukan Reyog Dhodhog berperan dalam mengiringi prosesi pembawa “gunungan”, dari balai dusun menuju balai desa. Dalam konteks ini, Reyog Dhodhog juga dapat dikategorikan sebagai tari upacara, yang menampilkan bentuk pertunjukan simbolik-representatif.
Saat prosesi pembawa gunungan berlangsung, masyarakat sekitar turut serta dalam perayaan ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Tidak hanya para petani yang merayakan hasil panen, tetapi juga para pedagang yang ngalap berkah.Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani, perayaan ini tetap menjadi momen kebahagiaan bersama, karena setiap orang bisa merasakan manfaat dari rasulan (bersih desa).
Antara Ingatan, Tradisi, dan Esensi yang Harus Dilestarikan
Reyog Dhodhog, dengan gerakannya yang merakyat, memberikan kegembiraan tersendiri bagi para among tani, bocah-bocah cilik, penjual es, penjual pecel. Masing-masing memiliki cara menontonnya sendiri, reflektivitasnya sendiri-sendiri, yang orang-orang sing kadhung ngutha seperti saya sulit sampai ke sana. Kesederhanaan yang justru maglung-maglung. Setiap bunyi bendhe berdenting, ingatan masa kecil saya yang sempat dicuri kota itu kembali. Ingatan tentang halusnya jarik Penthul, yang diusap ke wajah kecil saya, masih begitu terasa.
Ingatan memang ahlinya mengetuk hati. Dulu, mata kecil saya mungkin lebih tulus dalam menikmati Reyog Dhodhog dibandingkan sekarang. Saat masih kanak-kanak, saya melihatnya bukan sebagai sekadar pertunjukan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri.
Bahkan di langit sekalipun, saya bisa melihat seni yang hidup, ketika sebuah balon terbang diiringi tabuhan kendhang, lalu lalang ibu-ibu yang memikul tenggok, atau simbah yang dengan tenang menyeimbangkan sarang di kepalanya. Harumnya sega gurih, balungan, dan trancam menyatu dalam suasana. Segalanya menjadi bagian dari narasi yang lebih besar, di mana batas antara pertunjukan dan rasa syukur melebur, membentuk kesadaran yang lebih tinggi: kebudayaan.
Di ruang inilah esensi Reyog Dhodhog berada—sebuah warisan yang tidak boleh hilang, melainkan harus diturunkan kepada anak-cucu kita. Ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi sebuah identitas, sebuah tradisi yang mengajarkan kita tentang rasa memiliki, kebersamaan, dan spiritualitas. Karena pada akhirnya, Reyog Dhodhog bukan hanya milik generasi terdahulu, tetapi juga milik masyarakat secara terus menerus.
Cekap semanten atur kula, menawi wonten kirang langkungipun atur, nyuwun agunging pangaksami.
Pong jing pong, pong jing pong jung !
Digubah Oleh: Bagong Gugat
Editor: Sintas Mahardika
![]()
Kretekus dan tenaga luwes.
Oleh: Bagong Gugat